Kata
(Alfy
Maghfira)
 |
| sumber: 10-themes.com |
Maudy
merasa benci saat sinar matahari membelai wajahnya. Cahaya-cahaya itu
menembus bebas kaca jendela kamarnya. Dia merusak tidurnya, dia merusak
mimpinya, dia terus saja membangunkannya. Maudy mengerang, untuk beberapa saat ia
memicing marah pada sang mega yang selalu angkuh menghardik mimpinya. Kenapa harus
ada matahari?
“Kapan sih dunia ini kiamat?!”
Pantulannya terlihat di cermin yang
tergantung di dinding. Ia kusut masai. Air mukanya keruh. Sorot matanya pun
bergemuruh. Maudy melihat kenangan buruk dari lensa matanya. Ada banyak mozaik
kehidupan yang tersimpan dari dalam. Maudy mengepal kedua tangan. Seberapa keras
pun ia bersikap defensif, tetap saja ia akan jatuh lagi. Jatuh ke dalam
kebencian.
“Maudy! Sudah bangun?” Suara Mama
terdengar samar dari balik pintu. Maudy menatap sarkas pintu kamarnya yang bercat
merah. Warna yang serupa dengan emosinya akhir-akhir ini.
Meskipun matahari terus bersinar, langit masih
berwarna biru terang, burung-burung masih senang berkicau, dan angin masih
terasa sejuk, tapi Maudy... kehilangan senyumnya. Ia tak pernah bisa membual
lagi di depan banyak orang. Hatinya tak selapang cakrawala, ia begitu sempit
untuk menerima sebuah kata sederhana di hidupnya.
“Maudy...,” Mama kembali lagi
menyapa. Sekarang ketukan pintu terdengar membantu suara Mama.
Airmata Maudy hampir tandus. Tentu saja,
ia sudah mengurasnya selama satu minggu ini setelah mendengar kabar yang
membuat segala dunianya terasa kiamat. Mimpi-mimpinya seperti meteor-meteor
yang berjatuhan, meluluh lantahkan dunianya.
***
Hari
ini Maudy masih berbalut seragam putih-abu-abu, ia baru saja keluar dari
gerbang sekolah. Biasanya Maudy sering pulang bareng teman sekelasnya naik busway, tapi tiba-tiba Bang Atma—kakak tertua
Maudy—sudah nangkring bareng Jazz hitamnya, buat menjemput Maudy. Maudy merasa
heran, ada badai apa nih, enggak
biasanya.
Bang Atma berpose malas-malasan di
depan mobilnya. Ia menyandarkan punggung sembari bersedekap, bermuka kecut. Tak
segaris pun senyum tersungging dari bibirnya. Maudy tidak menampik, walaupun
abangnya terlihat urakan, tapi gestur wajahnya gak kalah ganteng sama Dimas
Anggara.
Abang
gue emang agak gesrek. Ngapain sih pasang wajah gitu. Senyum dikit, kek. Asem
banget!
Datang-datang
Maudy pun enggak kalah kecut wajahnya dari Bang Atma. “Ada apaan nih, baru kesambar
geledek, ya?” Cukup memuakkan juga nada ketus Maudy di telinga Bang Atma.
“Udah, deh, mending lu cepet masuk. Ntar lu juga tahu sendiri. Dan... gue
harap sih, adek gue yang masih dedek-dedek gemes ini enggak nangis seember pas
pulang ke rumah,” timpal Bang Atma setengah tertawa hambar di depan Maudy.
“Apaan sih, Bang?!” Wajah Maudy
merengut. Justru mulut abangnya itu udah bikin Maudy penasaran sepanjang jalan.
Tapi beruntung, mood Maudy hari ini
sedang secerah pelangi.
Ucapan Kak Yoga—cowok yang ia sukai—terus
ter-paste di otaknya, kemarin ia
sempat ketemu cowok berkacamata itu di Bareto Coffee, dia bilang begini, “Dek Maudy, besok-besok enggak usah
repot-repot datang ke sini. Nanti Kakak bakal ngajar di rumah Maudy.”
Sepanjang hari ini, Maudy kehilangan
kewarasannya. Senyam-senyum sendiri, sampai mukanya matang kayak habis
dipanggang.
“Dek, yang tabah, ya,” tiba-tiba
Bang Atma berceletuk aneh saat Jazz-nya berhenti tepat di depan muka rumah
didominasi cat hijau muda.
Suasana rumah terlihat tidak
biasanya. Sekarang ramai dipadati beberapa mobil kerabat jauhnya. Mama lagi ngadain syukuran, ya. Maudy
masih sepolos kanvas tak berwarna, ia tak pernah menduga apa pun, takdir apa
yang kan terlukis di kanvas kehidupannya. Ia hanya tahu, bahwa ia sendirilah
yang sedang berusaha melukis kanvasnya dengan mimpi-mimpinya.
“Ikhlas, ya, Dek!” Bang Atma menepuk
bahu Maudy. Lantas ia segera ke dalam rumahnya. Terlihat banyak tamu
yang tengah berbincang bersama kedua orangtuanya.
Maudy semakin keheranan melihat
semua orang berpakaian formal, apalagi Mama, “Kok Mama pakai kebaya, sih?”
Maudy menatap Mama dari atas hingga ke bawah, kemudian menangkap busana Papa
yang tidak kalah formal, “Papa juga. Memang mau ke kondangan, ya?”
Mama membelai puncak kepala Maudy
yang dibingkai rambut hitamnya yang jatuh sepinggang. “Maudy, maaf, ya, Mama
enggak bilang-bilang.”
“Bilang apaan sih, Ma?”
“Kamu pasti senang, Nak. Tuh lihat
Kak Renata.” Mama menunjuk seorang perempuan yang familier, tapi hari ini
penampilannya berbeda jauh dari biasanya.
Kak
Renata memang cantik, tapi... melihat rambutnya yang tersanggul, badannya
melekuk indah dibalut gaun birunya yang menyempit hingga pinggang dan
mengembang di atas paha, membuat Maudy semakin dihujani tanda tanya, ada apa
sebenarnya?
“Hari
ini kakakmu mau dilamar sama Yoga, dia kan yang sering nemenin kamu belajar,”
papar Mama sembari menatap haru Kak Renata yang terduduk malu di sudut ruangan,
tanpa menyadari ekspresi Maudy yang berubah keruh mendengar nama itu terlontar
dari lidah mamanya.
Ikhlas, ya, Dek!
Bolamata
Maudy yang serupa buah zaitun, terlihat mengembun. Ia mencari-cari keberadaan
Bang Atma. Cewek itu merasakan hatinya seakan ditusuk-tusuk sembilu, kata-kata
ikhlas Bang Atma, menyadari akan satu hal. Ia harus ikhlas melepaskan seseorang
yang dicintainya untuk kakaknya sendiri. Maudy berhasil menangkap raut muka
Bang Atma yang berbeda dari semua orang, hanya dia yang tahu perasaan Maudy
saat ini. Bang Atma tampak mengangguk. Maudy
tahu, Abang menyuruh Maudy tegar dan ikhlas, bukan?
***
“Maudy...
Mama tahu kamu masih terluka, Nak. Tapi Mama harap kamu bisa ikhlas. Maafin
Mama, ya, Nak. Mama harap Maudy mau memaafkan Kak Renata dan Kak Yoga,” Mama
terus berjuang di balik pintu kamar kokoh Maudy agar anaknya lekas bangun dan
menata hidupnya.
Mama, ikhlas memang mudah
dikatakan di lidah. Tapi itu bukan ikhlas, Ma. Maudy akan bangun jika ‘ikhlas’
sudah bisa diterima di hati Maudy, Ma. Maafin, Maudy, Ma. Aku belum ikhlas atas
segalanya....
Tasikmalaya,
28 Januari 2016
#KampusFiksi
#Ikhlas



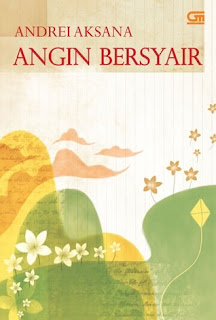








![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](valid-atom.png)